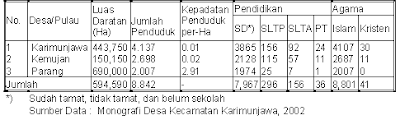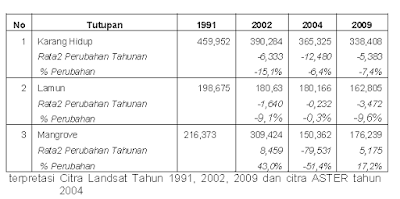1.
Pendahuluan
Kepulauan Karimun Jawa secara geografis terletak
di Provinsi Jawa Tengah dan telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut
Karimun Jawa berdasarkan SK. Menhut Nomor
74/Kpts-II/2001; Tgl 15-3-2001. Pulau Karimunjawa (ekosistem hutan hujan tropis
dataran rendah) 1.285,50 ha, dan wilayah perairan 110.117,30 ha. Kepulauan Karimun Jawa memiliki luas
107.225 ha, yang terdiri dari lautan seluas 100.105 ha, dan daratan seluas
7.120 ha yang tersebar di 27 pulau. Dari 27 pulau tersebut, 5 diantaranya telah
berpenghuni yaitu P. Karimunjawa, P. Kemujan, P. Parang, P. Nyamuk dan
P.Genting. Pulau-pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional
Karimunjawa terdiri dari 22 pulau, sedangkan 5 pulau lainnya tidak termasuk ke
dalam kawasan tersebut, yaitu P. Genting, P. Sambangan, P. Seruni, P.
Cendikian, dan P. Gundul (Yusuf, 2013).

TN
Karimunjawa mempunyai luasan total 111.625 ha, terdiri dari wilayah daratan di
Pulau Kemujan (ekosistem mangrove) 222,20 ha. Kawasan TN Karimunjawa terdapat
lima tipe ekosistem yaitu ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, hutan
pantai, hutan bakau, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang.
Berbagai upaya identifikasi dan invetarisasi flora dan fauna telah dilakukan
baik oleh Balai Taman Nasional Karimun Jawa (BTNKJ) maupun oleh instansi
terkait. Berdasarkan jenis habitatnya, saat ini telah teridentifikasi 262
spesies flora yang terdiri atas 171 flora yang hidup hutan hujan tropis dataran
rendah (151 flora hutan hujan tropis, 11 spesies lumut, 15 spesies jamur), 45
spesies mangrove, 34 spesies flora hutan pantai, 11 spesie lamun, 18 spesies
rumput laut. Sedangkan untuk fauna, saat ini telah teridentifikasi 897
spesies/genus fauna yang tersusun atas beberapa taxa yaitu Mamalia (7), Aves (116), Reptilia
(13), Insekta (42), Pisces (412),Anthozoa (182 skeleractinian dan 23 non
skeleractinian), Plathyhelminthes (2), Annelida (2),Gastropoda (47), Bivalvia
(8), Cephalopoda (7), Arthopoda (5), Echinodermata (31) (KKP, 2013).
1.
Kondisi Kep. Karimun Jawa
1.2.1.
Kondisi
Fisik dan Alam
Selain kondisi alam yang bagus, kep. Karimun Jawa
juga didukung kondisi fisik yang bagus. Iklim di kep. Karimun Jawa termasuk ke
dalam tipw C dengan curah hujan 3.000 mm/th dan suhu antara 30-310C.
kondisi oseanografi kawasan tersebut rata-rata kecepatan arus adalah 8-25 cm/dt.
Kondisi topografi adalah berupa dataran rendah yang bergelombang dan ketinggian
antara 0-506 m dari permukaan laut. Kondisi hidrologi kawasan Taman Nasional
Karimunjawa tidak terdapat sungai besar, namun terdapat lima mata air besar,
yaitu Kapuran (Pancuran Belakang), Legon Goprak, Legon Lele, Cikmas dan
Nyamplungan, yang dimanfaatkan sebagai sumber air minum dan memasak oleh
masyarakat sekitar (Supriharyono, 2003).
Fakta di lapangan, keberadaan pulau-pulau kecil di
kawasan TN Karimun Jawa sangat strategis sebagai salah satu sumber ekonomi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kepulauan Karimun Jawa
yang masih sangat bagus menambal nilai ekonomis kawasan tersebut. Pada
kepulauan Karimun Jawa dapat dijumpai berbagai macam ekosistem laut
diantaranya: ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, dan ekosistem padang
lamun. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang subur dan paling
produktif di lautan, hal ini disebabkan oleh kemampuan terumbu untuk menahan
nutrien dalam sistem dan berperan sebagai kolam untuk menampung segala masukan
dari luar. Yusuf (2013) menyebutkan kondisi terumbu karang di Kep. Karimun Jawa
terdapat 20-33 genus. Jumlah terbesar ditemukan di P. Tengah, P. Kecil, P.
Krakal Kecil dan P. Kumbang, sedangkan yang terendah ditemukan di P. Kemujan,
dan P. Menyawakan. Kepadatan ikan-ikan karang yang didapatkan di perairan
Karimunjawa berkisar antara 0,5–3,2 ekor/m2 atau ratarata sebesar 1,14 ekor/m2.
Kepadatan terendah ditemukan di P. Menjangan Kecil dan tertinggi di P. Sintok
dengan total potensi sumberdaya ikan adalah 653,1 ton/th.
Ekosistem hutan mangrove Taman Nasional Karimunjawa
terdapat di Pulau Karimunjawa, Kemujan, Cemara Kecil, Cemara Besar, Krakal
Kecil, Krakal Besar, Mrico, Menyawakan, dan Sintok. Hutan mangrove terluas
terdapat di Pulau Kemujan dan Karimunjawa seluas 396,90 ha yang didominasi oleh
jenis Exoccaria agallocha sedangkan jenis Rhizhophora stylosa menyebar
di seluruh wilayah. Spesies mangrove yang ditemukan di Karimunjawa terdiri dari
44 spesies yang terdiri atas 26 spesies mangrove sejati dan 13 spesies mangrove
ikutan yang berada di dalam kawasan dan 5 spesies di luar kawasan taman
nasional. Padang lamun tersebar diseluruh kawasan taman nasional hingga
kedalaman 25 m. Jenis lamun yang ditemukan sebanyak 9 jenis yaitu Enhalus
acroides, Halophila ovalis, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata,
C.Serulata, Halodule pinifolia, H.univervis, Syringodium isotifolium, dan Thalassodendrum
ciliatum. Dengan persentase penutupan dan kerapatan relatif cukup banyak
pada jenis Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, dan Halophila
ovalis (Anggraeni, 2008).
1.2.2.
Kondisi
Sosial
Berdasarkan Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa
Tahun 2002, kawasan Taman Nasional Karimunjawa dihuni penduduk sebanyak 8.842
jiwa. Tingkat pendidikan di Kepulauan Karimunjawa lebih banyak tamat, tidak
tamat dan belum sekolah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan
karena penduduk usia sekolah banyak bekerja membantu orang tua, rendahnya
kesadaran dan keterbatasan biaya.
Mata
pencaharian masyarakat karimunjawa didominasi oleh buruh tani/nelayan yaitu
sebesar 61%. Hal ini mengindikasikan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap
sumberdaya perikanan. Masyarakat
Karimunjawa berasal dari etnis Jawa, Madura, Bajo, Bugis, Muna, Luwu,
Buton dan Mandar. Mayoritas penduduk Karimunjawa berasal dari Jawa, namun
sebagian besar etnis telah berbaur dan berinteraksi dengan etnis lain. Salah
satu kebiasaan warga karimunjawa pada setiap Kamis malam adalah mengadakan
acara tahlillan secara bergilir di setiap lingkungan dengan tujuan mempererat
silaturahmi.
1.
Rencana Pengembangan Kep. Karimun Jawa
Kepulauan
Karimun Jawa memiliki kondisi alam yang sangat bagus dan memiliki kearifan
masyarakat yang pro aktif dalam pembangunan dan pengembangan kawasan konservasi
TN Karimun Jawa. Dengan kondisi alam dan masyarakat yang dinamis dan aktif,
maka pengembangan dan pembangunan daerah Kep. Karimun Jawa adalah sebagai
kawasan konservasi dan ekowisata secara terpadu berbasis masyarakat. Menurut
Balai Taman Nasional Karimun Jawa (2004) visi utama pengembangan TN Karimun
Jawa adalah memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dengan
melestarikan fungsi ekosistem menuju terwujudnya hubungan yang seimbang,
seriasi, selaras antara manusia dan lingkungannya yang dapat mendukung
pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan karimunjawa.
Keterpaduan dan
integrasi Kep. Karimun Jawa dapat dicapai dengan adanya 1.) keberadaan
sumberdaya pesisir dan lautan yang besar dan beragam, 2.) peningkatan
pembangunan dan jumlah penduduk, 3.) tuntutan keseimbangan antara kepentingan
konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan sebagai pusat
pengembangan kegiatan ekonomi dalam proses pembangunan. Pengembangan aspek
sosial, ekonomi, dan budaya: dilakukan secara berkelanjutan dan dinamis dengan
mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspirasi masyarakat serta
konflik kepentingan dan pemanfaatan yang mungkin ada. Integrasi dan keterpaduan
pengelolaan Kep. Karimun Jawa meliputi beberapa hal diataranya: aspek ekologis,
sektor, multi disiplin ilmu, stakeholder, dan private sector. Pendekatan
keterpaduan pengelolaan/pemanfaatan kawasan kep. Karimunjawa menjadi sangat
penting, sehingga diharapkan dapat terwujud satu rencana dan satu pengelolaan
serta tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan.
Balai
Taman Nasional Karimun Jawa (2004) menentukan arah kebijakan pengelolaan Kep.
Karimun Jawa menjadi 5 arah kebijakan. Kebijakan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Kebijakan
pemberdayaan masyarakat (memperkuat peran penduduk asli, dan pembangunan
ekonomi masyarakat)
2.
Kebijakan
konservasi lingkungan biofisik
3.
Kebijakan sistem
pemanfaatan zona
4.
Kebijakan
pengembangan pariwisata bahari terpadu
5.
Kebijakan
pengembangan kelembagaan dan pembiayaan.
2.
Pengembangan
Sektor Ekowisata Kep. Karimun Jawa
Sektor pariwisata adalah sektor pendongkrak roda
perekonomian. Sektor pariwisata mampu memberikan sumbangan besar bagi
perkembangan kehidupan masyarakat sekitar. Sektor wisata dipadupadankan dengan
ekologis menajdi ekowisata. Konsep ekowisata diharapkan mampu menggerakan roda
ekonomi dengan tetap ramah terhadap lingkungan. Pembangunan Kep. Karimunjawa
harus mampu mengakomodir dua hal penting, yaitu kesejahteraan masyarakat dan
kelestarian lingkungan. Oleh karenanya pembangunan Karimunjawa harus memiliki
manfaat terbesar untuk masyarakat. Orientasi pengembangan harus memiliki
keseimbangan kepentingan antara ekonomi dan konservasi dan seluruh rangkaian
proses dari pengembangan sampai dengan pembangunan melibatkan masyarakat dan stakeholder
terkait. Pariwisata dikembangkan dengan menggunakan prinsip sebagai
berikut:
1.
Pariwisata
sebagai industri,
2.
Pariwisata
berkelanjutan
3.
Pariwisata
sebagai pengembangan wilayah
4.
Keterpaduan
sistem permintaan dan penawaran
5.
pemberdayaan
masyarakat lokal
6.
Sinergis dan
komplementasi
Tampaknya, konsep ekowisata (eco-tourism)
hanya menjadi wacana belaka. Konsep ini hanya sebagai konsep, tetapi pada
kenyataan lapang tetap menimbulkan masalah degradasi lingkungan. Secara umum,
fungsi utama kawasan taman nasional adalah sebagai daerah perlindungan
sumberdaya alam hayati dan non hayati. Kerusakan lingkungan dari proses
penangkapan ikan yang kurang ramah lingkungan, waste management yang
kurang bagus ditambah dengan jumlah wisatawan yang semakin besar.
Degradasi yang terjadi dapat dilihat dari tabel di bawah menurut
Suryanti (2010):
Data di atas merupakan data yang didapat dari
analisa citra satelit dalam skala periode waktu. Data didapat dari perbandingan
tahun 1991, 2002, 2004, dan 2009. Terdapat perubahan yang signifikan dari tahun
1991 hingga tahun 2002. Ekosistem karang hidup mengalami degradasi sebesar
15,1%, lamun sebesar 9,1%, dan mangrove mengalami perluasan 43,0%. Tahun
2002-2004 degradasi 6,4%, 0,3%, dan 51,4% untuk karang hidup, lamun, dan
mangrove. Kondisi ini terus berlangsung dari waktu ke waktu hingga saat ini.
Dari data diatas, ekowisata memang cara baik untuk
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Akan tetapi, fakta di lapang ekowisata
masih tidak bisa menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan ekologi. Dengan
demikian TN Karimun Jawa, kabupaten Jepara harus dikembalikan ke tujuan semula
untuk tujuan konservasi dan perlindungan lingkungan.
REFERENSI
Anggraeni,
R. 2008. Valuasi Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang Taman Nasional Karimunjawa.
Bogor: Institut Pertanian Bogor.
BTNKJ.
2004. Penataan Zonasi Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara Provinsi
Jawa Tengah. Semarang: Departemen Kehutanan.
KKP.
2013. Basis Data Konservasi. (http://kkji.kp3k.kkp.go.id/
index.php/basisdata- kawasan-konservasi/details/1/13). Diakses pada 28
September 2015 Pukul 16.59.
Supriharyono.
2003. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Suryanti.
2010. Degradasi Pantai Berbasis Ekosistem di Pulau Karimun Jawa Kabupaten
Jepara. Semarang: Universitas Diponegoro.
Yusuf,
M. 2013. Kondisi Terumbu Karang dan Potensi Ikan di Perairan Taman Nasional
Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Semarang: Universitas Diponegoro.